
“Cita-citaku… (cita-citaku), ingin jadi presiden… ”
Masih ingat dengan lagunya Susan dan Ria Enes yang itu? Sangat familiar tentunya. Renyah didengar, menggelitik, dan ’anak-anak banget’.
Cita-cita, sebuah kata yang selalu ditanyakan saat kita masih kecil dulu, jawabannya pun beragam dan berubah-ubah, ingin jadi dokter lah, jadi insinyur lah, jadi presiden, jadi guru, jadi pilot, dan lain sebagainya. Sah-sah saja, toh dulu ketika kecil aku juga seperti itu. Masih ingat sekali saat itu aku selalu menjawab ”ingin jadi dokter”, kadang juga bilang ”ingin jadi polwan ”. Semua orang juga begitu tentunya?!.
Bagaimana dengan keinginan untuk menjadi presiden? Juga tidak sedikit anak-anak yang mencita-citakannya, dan semua itu terdengar lumrah saat keluar dari mulut mungil anak kecil. Tapi pernahkah di usia matang seperti saat ini kita mengucapkan cita-cita ingin menjadi seorang presiden (meskipun dalam hati)?
Aku pernah! Serius! Aku pernah mengucapkannya. Dan bukan cuma main-main! Meski tidak berlangsung lama keinginan itu muncul, tapi kalimat itu keluar bukan sebagai gurauan, bukan juga igauan, kalimat itu muncul sebagai klimaks dari sebuah keresahan yang saat itu dengan hebat melanda alam fikirku.
Tepatnya di pertengahan tahun 2008, saat aku iseng-iseng ikut bergabung dengan teman-teman yang lain menjadi suveyor untuk Lembaga Survey Indonesia (LSI), survey tentang sosial kemasyarakatan di propinsi Jawa Barat saat itu menugaskanku berada di sebuah desa kecil di daerah Bogor. Sebuah desa yang telah membuatku jatuh cinta dengan keramahan warganya. Luar biasa! Sebagai seorang pendatang yang tak punya satupun sanak maupun kerabat dan bahkan baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi itu, dengan kepentingan yang barangkali menurut orang desa dianggap ”apaan sih? ”, tapi betapa mengagumkan masyarakatnya, aku diterima dengan begitu ramahnya, dilayani dengan begitu khidmatnya, dan dihargai dengan begitu mempesonanya.
Pokoknya, ”Wonderful”
Selama tiga hari dua malam aku berada di sana, menginap di rumah salah seorang warga yang mengaku juga punya anak yang kuliah di UIN Jakarta (tempat kuliahku saat itu). Pagi, siang, sore, hingga malam aku berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain sesuai hasil random pemilihan sample penelitian yang telah kuhitung sedemikian rupa, jumlahnya ada 20 rumah (belum termasuk rumah pak lurah, beberapa rumah pak RW dan beberapa rumah Pak RT untuk pendataan sebelum dilakukan random, juga minta ijin plus tanda tangan dan stempel tentunya).
Satu per satu responden telah kuambil datanya, di masing-masingnya melekatkan cerita tersendiri yang senantiasa membuatku rindu kepayang dengan mengingatnya. Hingga sampailah aku pada responden yang kesekian. Seperti biasa, aku disambut dengan keramahan dan binar wajah dari pak RT setempat, kuutarakan maksudku untuk meminta data warganya untuk kemudian dirandom dan diambil datanya, beliau menurut. Ditemani segelas air putih, aku mulai menulis data warga di lembar kertas yang kuambil dari dalam map yang kubawa, dengan sabar beliau menungguiku yang berkutat dengan kertas-kertas di hadapanku, menghitung, mengurutkan, menandai, dan seterusnya. Tentu saja tidak hanya dengan diam membisu, sesekali aku bertanya tentang ini dan itu, dan beliaupun menjawabnya dengan nada tulus dan sama sekali tanpa beban. Kerenlah pokoknya!
Setelah selesai merandom dan aku sudah kembali tegak di posisi dudukku, mulailah dia bercerita lebih leluasa. Mulai dari keluarganya, anaknya yang sudah berkeluarga hingga saat cucunya berusia SMA masih tinggal bersama dengannya dan menempati sebuah kamar berukuran 2,5 x 3 meter. Kemudian, tentang warganya yang baru saja menerima kompor hasil konversi minyak tanah ke gas yang digagas pemerintah dengan segala permasalahannya. Hingga soal BLT yang alih-alih memberi kesejahteraan warganya malah dianggapnya menimbulkan kecemburuan sosial karena pada kenyataannya tidak tepat sasaran, dan lain sebagainya.
Srrr...! darahku berdesir mendengar penuturan miris dari mulut pria berusia kurang lebih 60 tahun ini. Tampaknya bapak di depanku ini ’membaca’ panampilanku dan dikiranya aku adalah pegawai pemerintahan yang punya kesempatan untuk menyampaikan keluhannya kepada pemerintah. Tuhan, akan Engkau selipkan amanah apakah sampai aku harus mendengar ini semua? . Perlahan, aku mulai merasa air sudah berkumpul di sudut mataku, aku ingin menangis, terlebih saat aku diantar oleh Bu RT menemui warga yang kusebutkan masuk sebagai respondenku, begitu masuk rumah sederhana itu tanganku langsung diraih dan diajak untuk melihat keadaan rumahnya yang sangat tidak layak, dengan kondisi dapur yang beratapkan langit karena gentingnya sudah enggan lagi berjibaku dengan terik mentari.
Hatiku gerimis, menyaksikan betapa kondisi ini baru pertama kali kulihat di depan mataku, kuinjak dengan kakiku, dan kudengar keluhan miris langsung dari aktor utamanya dengan telingaku sendiri. Ilahi, rahasia apa yang Kau simpan di balik takdir-Mu untuk mereka? Tiba-tiba saja aku teringat pemimpin dari rakyat yang ada di hadapanku ini, pemimpin yang mereka pilih dan titipkan amanah besar dipundaknya, pemimpin yang berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi mereka. Pernahkah pemimpin mereka dengan mata kepalanya menyaksikan apa yang kusaksikan hari ini? Oh, I don’t think so.
Dadaku bergemuruh, sakit, miris, sedih, marah, berebut memenuhi rongga dada, membuncah, mancabik, meletup-letup, hingga memuntahkan sebuah kalimat pamungkas,
”AKU INGIN JADI PRESIDEN ”
Hhh...! lega rasanya, akhirnya kalimat itulah yang keluar. Meski tak tau arti dari kalimatku sendiri, tapi setidaknya keresahan hebat itu menemukan klimaksnya, tidak mengantung-gantung, meronta-ronta menunggu jawaban hingga berlarut-larut. Entahlah, apa yang saat itu berkecamuk di alam fikirku, yang kuingat hanyalah bahwa aku ingin berbuat sesuatu, tidak mungkin Allah memberiku kesempatan bertemu dan mendengarkan keluhan mereka jika Aku tak diminta untuk berbuat sesuatu.
Menjadi seorang presiden, bukan keinginan yang kecil tentunya. Dan benakku pun sama sekali tak pernah mampu meski hanya membayangkannya, jauh, sangat jauh. Dan hingga akhirnya, keinginan itu pun luruh oleh waktu.
Tapi, benarkah pengalaman sedemikian dramatis tak memberi bekas apapun dalam kehidupanku seiring tak berlanjutnya cita-cita? Tidak! Tidak benar! Pengalaman itu telah membekaskan sebuah ukiran di seluruh persendianku. Meski tidak dengan melanjutkan keinginan menjadi presiden, tapi semua itu kini membelalakkan mataku yang bertahun-tahun kututup karena telah terlalu apatisnya dengan yang namanya pesta demokrasi di Indonesia.
Iya, benar. Aku tak pernah sekali pun ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi di negeri ini sebelumnya, di tingkat manapun, daerah ataupun pusat. Tapi kali ini, aku benar-benar ingin memberikan suaraku kepada seseorang yang kuanggap paling mampu mengemban amanah besar ini. Aku ingin menitipkan negeri ini kepada pemimpin yang benar-benar manjadikan kesejahteraan rakyat sebagai aliran darahnya. Dan akhirnya, aku pun menemukannya. Tak satupun orang di sekelilingku yang tak menertawakan pilihanku, tapi aku tak peduli, aku telah menelusuri rekam jejak kehidupannya, aku mencoba mempelajari karakteristik dan gaya kepemimpinannya, dan aku pun memilihnya karena hatiku mengatakan dialah orang yang paling tulus diantara kandidat yang ada, tulus ingin memberikan perubahan atas negerinya yang selama ini terbuai dan terlelap dalam ketidakadilan.
Meski akhirnya, KALAH!!!
Tak apalah, inilah demokrasi. Dan kini, aku tetap tak boleh berhenti, aku tetap harus berbuat sesuatu, sebanyak-banyaknya, meski tak mampu berbuat dalam skala makro seperti seorang presiden dengan kebijakan dan undang-undangnya, tapi setidaknya aku bisa berusaha menjadi ummat Muhammad yang melaju mengejar ”Khoirunnas anfa’uhum linnas ” (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya).
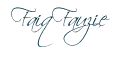
0 comments:
Posting Komentar