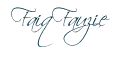Cerita ini udah hadir lewat facebook dan kompasiana meskipun ditulis oleh Tempo 4 tahun yg lalu. Berikut ceritanya:
Tiga Hari Penuh Badai
Inilah kisah di pusat kekuasaan selama tiga hari pertama setelah tsunami. Mengenang setahun tragedi itu, beberapa sumber termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Komunikasi dan Informasi Sofjan Djalil menuturkan kenang-kenangan mereka kepada Tempo.
****
Baru duduk di jok mobilnya, telepon seluler Jusuf Kalla berdering-dering. Staf pribadinya melaporkan: “Pak, di Aceh ada tsunami. Dahsyat sekali.” Pagi itu, 26 Desember 2004, Kalla hendak menghadiri halal bihalal warga Aceh di Senayan, Jakarta. Kalla lalu mengirim pesan pendek ke telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pagi itu berada nun jauh di Nabire, Papua. Presiden menemui korban gempa yang melumat Nabire sehari sebelumnya.
Presiden membalas: “Saya sudah dengar. Tolong koordinasikan.” Kalla lalu menelepon Azwar Abubakar, Wakil Gubernur Provinsi Aceh. Gubernur Abdullah Puteh saat itu telah ditahan di penjara Salemba karena dugaan kasus korupsi.
Kalla juga mengontak Kapten Didit Soerjadi, pilot pesawat pribadinya. Didit sedang beristirahat. “Kau segera mandi dan berangkat ke Aceh,” perintah Kalla. Semuanya serba buru-buru. Perintah terus mengalir saat Didit mandi. “Lucu juga, saya mandi sambil terima telepon Pak Wapres,” kenang sang pilot. Wapres menggegas semua stafnya menelepon semua pejabat di Aceh. Sial, tak satu pun menyahut. Kalla mulai cemas.
Di Aceh, dunia berhenti pagi itu. Bumi berguncang dengan kekuatan 8,6 pada skala Richter, air laut tumpah ke daratan. Beberapa keluarga sempat mengabarkan soal air bah kepada kerabat di Jakarta. Cuma sebentar. Lalu telepon putus total.
Halal bihalal warga Aceh di Senayan dibuka pada pukul sembilan lebih, berlangsung dalam suasana tegang sekali. Berita tsunami sudah menyebar. Banyak yang sibuk menelepon. Beberapa orang berlinang air mata. Ada yang histeris, gusar kian-kemari. Kalla berpidato sekenanya. Hampir tak ada yang mendengar. “Orang-orang ingin acara itu cepat kelar,” tutur Kalla kepada Tempo. Turun panggung, Kalla menggelar rapat mendadak di situ.
Dia memerintahkan Sofjan Djalil memimpin rombongan pertama ke Aceh. “Pakai pesawat saya saja,” kata Wapres. Anggota rombongan 30 orang, antara lain Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Azhari, Azwar Abubakar, dan beberapa tetua Aceh. Kalla membekali Sofyan uang Rp 200 juta dan sebuah telepon satelit. “Begitu kau tiba di Aceh, langsung telepon saya,” perintahnya. Mereka menjadi rombongan pertama pemerintah yang terbang ke Aceh di hari pertama tsunami.
Pesawat berputar dua kali di langit Banda Aceh. “Dari udara Aceh terlihat hancur total,” tutur Kapten Didit. Menara bandara retak. Tak satu pun petugas di menara. Untung, pesawat mulus mendarat, sekitar pukul enam sore.
Anggota rombongan membeli beras dan mi instan di beberapa toko dekat bandara, lalu beranjak ke pendapa kantor gubernur sekitar pukul tujuh malam. Jalanan sunyi senyap. Gelap gulita. Satu-satunya penerangan cuma lampu mobil. Sungguh mengerikan. Mayat bergelimpangan di jalan, di kolong rumah, tersangkut di dahan pohon. Beberapa ekor anjing berlari ke sana kemari. Anggota rombongan mulai menangis sesenggukan.
Malam itu ratusan orang menumpuk di pendapa kantor gubernur. Banyak yang luka parah. Puluhan mayat dijejerkan di latar depan pendapa. Aceh lumpuh total. Koordinasi tak jalan karena aparat pemerintah pusing mencari sanak keluarga. Kepala Polres Banda Aceh hanyut ditelan tsunami.
Azwar Abubakar, Wakil Gubernur Aceh, bisa memimpin. Namun, dia sedang galau. Rumahnya di Blang Padang hancur. Ia tak tahu nasib anak-anaknya. Wakil Gubernur ini pulang ke rumahnya ditemani Sofjan Djalil, Jusuf Azhari dikawal dua tentara. Mobil melaju dalam gelap, menghindari mayat-mayat yang direbahkan di kiri-kanan jalan. Mobil berhenti kira-kira 50 meter dari rumah Azwar sebab sampah menggunung menutup jalan.
Wakil Gubernur turun ditemani seorang tentara. Dipandu nyala senter, mereka mengendap-endap. Sofjan menunggu dengan cemas. Setengah jam berlalu, Azwar pulang. “Di rumah banyak mayat, tapi anak-anakku tak kelihatan,” katanya penuh kecemasan. Mereka lalu balik ke pendapa.
Berkali-kali Sofjan menelepon Jusuf Kalla di Jakarta. Tak bersahut. Di Jakarta, Wapres menggelar sidang kabinet darurat di rumah dinas Jalan Diponegoro pada pukul 21.30 WIB. Sembilan menteri dan Panglima TNI hadir. Sembari rapat, Kalla berkali-kali pula mengontak Sofjan. Tak bersambung juga. “Sofjan itu bawa telepon satelit kok tidak sambung-sambung,” kata Kalla.
Di Aceh, Sofjan memutuskan mengirim kabar lewat Orari Angkatan Udara di Aceh. Orari Jakarta meneruskan pesan itu ke telepon seluler Jusuf Kalla. Ini laporan pertama Sofjan dari wilayah bencana: ”Pak, korban sekitar 5.000 hingga 6.000.” “Astagfirullah, astagfirullah,” kata Kalla berkali-kali sembari mengusap wajah. Sejumlah menteri tertunduk. Hening menyapu ruang rapat.
Kalla melanjutkan pesan ke Presiden Yudhoyono yang malam itu sudah tiba di Jayapura. Presiden menyampaikan belasungkawa kepada korban bencana. Besoknya, Presiden terbang menuju Aceh.
Pukul sepuluh malam, telepon satelit Sofjan sukses menembus Jakarta. “Eh, ini Sofjan,” ujar Kalla kegirangan. “Apa yang terjadi? Kenapa kau tak telepon-telepon?” tanya Kalla dengan suara keras. “Saya stres, Pak. Di sini gelap sekali,” sahut Sofjan dari seberang. “Besok aku susul ke sana,” ujar Kalla. Percakapan ditutup.
Malam itu Kalla mematangkan persiapan ke Aceh. “Saya minta Anda menyediakan dana sepuluh miliar uang kontan,” perintah Kalla kepada Menteri Keuangan Jusuf Anwar. Jusuf tertegun. “Pak, kalau segitu tak ada,” jawabnya. “Saya tidak mau tahu. Itu urusanmu,” kata Kalla. Rapat bubar larut malam.
Di larut malam itu, pendapa kantor gubernur di Banda Aceh masih gaduh. Warga yang luka parah dirawat seadanya. Koordinasi sulit karena aparat sibuk mencari keluarga masing-masing. Kepala Polda Aceh Bahrumsyah datang ke pendapa dengan terengah-engah. Wajahnya letih. Si Kapolda cuma mengenakan pakaian dinas tanpa alas kaki alias nyeker. Orang hilir-mudik di pendapa membikin Sofjan bingung menjaga uang Rp 200 juta yang dia bawa dari Jakarta. Ia meminta seorang anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera menjaga uang itu. “Orangnya berjenggot. Uang pasti aman,” ujar Sofjan.
Sang Menteri lalu merebahkan badan di atas karpet. Belum lagi mata terpejam, terdengar pekikan, “Gempa! Gempa!” Orang-orang berlari. Sofjan ikut kabur. Setelah bergoyang beberapa menit, bumi kembali tenang. Warga kembali ke pendapa. Tak berapa lama, teriakan gempa terdengar lagi. Semua berhamburan, termasuk Pak Menteri. Malam itu gempa datang berkali-kali. Lama-lama, Sofjan putus urat takutnya. Saat orang-orang kabur, ia terlelap. “Sudah jam dua pagi, masak lari-lari terus. Saya lelah sekali,” kenangnya. Besoknya, orang ramai menggunjingkan kehebatan nyali Pak Menteri.
*****
Hari kedua, 27 Desember. Entah bagaimana caranya, Menteri Keuangan berhasil menyediakan uang kontan pagi itu. Jumlah Rp 6 miliar. Menjelang siang, Kalla terbang ke Aceh membawa serta uang satu peti. Petang hari, Presiden Yudhoyono mendarat di Lhokseumawe. Wajahnya sedih. “Tadi pagi saya meninjau Nabire. Sore ini saya di Lhokseumawe menemui saudara-saudara yang tertimpa musibah lebih besar lagi,” katanya.
Setibanya di Banda Aceh, Kalla memerintahkan stafnya memborong beras, mi instan, dan aneka makanan lain. Karena berasnya kurang, Kalla bertanya, “Eh, berasnya sedikit sekali. Mana beras dari Dolog?” Seseorang menjawab, pintu Dolog digembok. Si pemegang kunci tak diketahui rimbanya. Wakil Presiden menyergah dalam nada tinggi “Buka! Kalau tak bisa, tembak gerendelnya. Apa perlu tanda tangan Wapres untuk buka pintu Dolog?” Suasana tegang. Beberapa polisi bergegas membidik gembok. Beras pun mengalir.
Rombongan Kalla berlalu ke pendapa kantor gubernur. Di Lambaro, mereka menyaksikan ratusan mayat berjejer di depan toko. “Masya Allah,” ucap Kalla. Badannya lemas. Di pendapa ia menggelar rapat, lalu keliling kota bersama Mar’ie Muhammad, Ketua Palang Merah Indonesia, yang datang sehari sebelumnya. Kota itu lautan mayat.
Mayat-mayat harus segera dikubur karena bau busuk menikam hidung. Untung, ada seorang ustad. Kalla minta ustad itu mendoakan tumpukan jenazah sebelum dikuburkan. Tapi siapa yang menjamin sahnya pemakaman? “Saya jamin,” kata Kalla. Ia mencorat-coret di atas kertas, lalu membubuhkan parafnya. “Tolong keluarkan ayat yang pantas-pantas saja,” pintanya kepada ustad.
Sore hari Kalla terbang dengan helikopter ke Lhok Nga untuk menjatuhkan mi instan dari udara. Helikopter itu tak punya sabuk pengaman. Setiap pesawat memutar, tubuh Kalla serong ke kiri, serong ke kanan. Rombongan Kalla terbang ke Medan pukul tujuh malam. Sofjan Djalil yang sudah dua hari di Banda Aceh minta ikut pulang. “Baru dua hari sudah minta pulang. Kau tetap di sini,” jawab Kalla. Malam itu Sofjan pusing tujuh keliling menjaga uang satu peti yang dibawa Kalla. Takut uang itu dicolong, Menteri Sofjan dan kawan-kawannya tidur mengitari peti itu.
*****
Hari ketiga, 28 Desember. Presiden Yuhdoyono terbang dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh. Kalla yang sudah berada di Medan mendapat kabar Meulaboh rata tanah. Ia memerintahkan stafnya mencari pesawat ke Meulaboh. Dapat pesawat Angkatan Udara. Dari udara, Meulaboh tampak seperti tanah gusuran. “Astagfirullah,” ucap Kalla berkali-kali.
Kalla meminta pilot terbang lebih rendah. Pilot mengangguk. Kalla minta lebih rendah lagi. Kali ini pilot bilang, “Tak bisa, Pak. Bahaya.” “Kau ini orang mana?” tanya Kalla. “Saya orang Makassar, Pak,” jawab si pilot. “Ah, orang Makassar kok penakut,” sergah Kalla. Pilot mengalah, pesawat melayang cuma beberapa meter di atas pucuk kelapa. Untung saja arahnya ke laut.
Setelah berkali-kali memutar di atas Meulaboh, pesawat kembali ke Medan. Kalla langsung rapat dengan Gubernur Sumatera Utara Rizal Nurdin—kini sudah almarhum. Dia memerintahkan Gubernur mengirim makanan ke Meulaboh. Keduanya sempat bersoal-jawab.
+ “Bagaimana caranya, Pak?” tanya Gubernur.
- “Lewat udara, buang dari pesawat,” jawab Kalla.
+ “Kalau dibuang nanti pecah, Pak.”
- “Tidak apa-apa, toh sampai di perut pecah juga.”
+ “Ya, tapi nanti basah Pak.”
- “Bungkus saja pakai plastik.”
+ “Pak, nanti jatuh ke GAM,” Gubernur berusaha menjelaskan.
- “ Tidak apa-apa. GAM juga manusia. Perlu makan,” nada Kalla mulai meninggi.
Beberapa orang membisiki Gubernur supaya jangan membantah.
+ “Jadi, bagaimana, bisa atau tidak?” tanya Kalla.
- “Siap, Pak,” jawab Gubernur.
Pesawat pemasok makanan melayang ke Meulaboh. Presiden dan Wakil Presiden kembali ke Jakarta pada hari ketiga.
Lalu, bantuan kemanusiaan mulai mengalir dari segenap penjuru dunia….